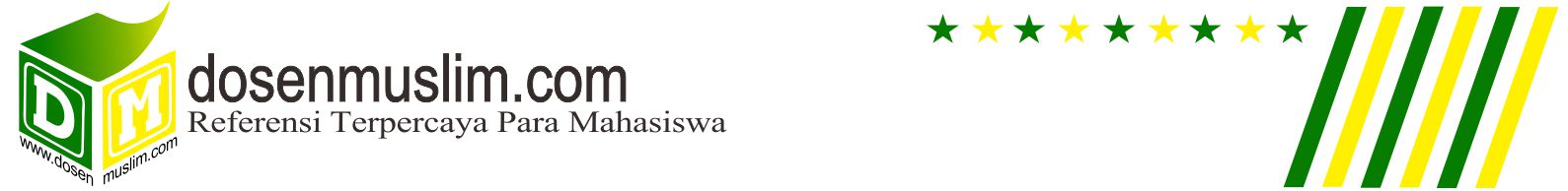Aliran Mu’tazilah
Pengertian Muktazilah
Perkataan “Mu’tazilah” berasal dari kata “i’tizal”, yang berarti penyisihan atau mengasingkan diri. Adapun kaum Mu’tazilah berarti kaum yang menyisihkan atau mengasingkan diri.[1]
Ada beberapa pendapat yang menerangkan latar belakang penamaan kelompok Mu’tazilah, yaitu sebagai berikut:
Seorang guru besar di Baghdad, bernama Syaikh Hasan Bashri (meninggal tahun 110 H) memiliki murid yang bernama Washil bin Atha’ (meninggal tahun 131 H). Pada suaut hari, Imam Hasan al-Bashri mengadakan halaqah di masjid Bashrah dan menerangkan bahwa orang islam yang telah beriman kepada Allah dan RasulNya, kemudian mengerjakan dosa besar, orang tersebut tetap muslim. Hanya saja, dia telah berbuat durhaka. Apabila meninggal dunia sebelum bertaubat, dia akan masuk neraka terlebih dahulu untuk menerima hukuman atas perbuatan dosanya. Akan tetapi, setelah menjalankan hukuman tersebut, dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga sebagai seorang mukmin dan muslim.
Washil bin Atha’ tidak sependapat dengan gurunya. Dia memberrontak dan mendirikan majelis tesendiri di pojokan masjid Bashrah itu. Sejak itulah, Washil bin Atha’ disebut sebagai Mu’tazilah karena mengasingkan diri dari gurunya. Dalam pengasingan diri itu, dia diikuti oleh seorang kawannya bernama Umar bin Ubeid (meninggal tahun 145 H).[2]
Sejarah tidak mencatat secara pasti mengenai tanggal, hari, dan bulannya, tetapi dapat dipastikan bahwa gerakan Washul nin Atha’ ini dimulai pada tahun 120 H, yakni ketika dia berusia 40 tahun, dan dia dilahirkan pada tahun 80 H. Jadi, dapat dikatakan bahwa permulaan munculnyapaham mu’tazilah ialah pada permulaan abad ke-2 dengan guru besarnya Washil bin Atha’ dan Umar bin Ubeid pada masa bani Umaiyah (tahun 100 H – 125 H).[3]
Ada pula yang mengaatakan bahwa latar belakang penamaan Mu’tazilah ialah karena pengasingannya dari masyarakat. Menurut pendapat ini, orang-orang Mu’tazilah, pada mulanya adalah orang-orang Syi’ah yang patah hati akibat menyerahnya Khalifah Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib kepada Khalifah Mu’awiyah dari bani Umaiyah.
Mereka mengasingkan diri dari siasah (politik) dan memfokuskan diri pada kegiatan ilmu pengetahuan. Kalau ucapan Tharaifi ini benar, tanggal permulaan gerakan Mu’tazilah ini adalah sekitar tahun 40 H, yakni ketika Hasan Menyerahkan pemerintahan kepada Mu’awiyah.
Tharaifi dan Muhammad Abu Zahrah tidak menerangkan nama orang-orang yang patah hati itu dan tidak menerangkan tahun-tahunnya. Oleh karena itu, dalil Tharaifi ini tidak begitu kuat, apalagi kalau dilihat dalam kenyataannya bahwa orang-orang Mu’tazilah dalam praktiknya bukan patah hati, melainkan justru banyak mencampuri soal-soal politik hingga mendominasi Khalifah Al-Makmun, Khalifah Al-Mu’tashim, dan Khalifah Al-Watsiq. Bahkan, di antara mereka, ada yang duduk mendampingi Kepala Negara sebagai penasihatnya.[4]
Ahmad Amin mengarang buku ‘Fjarul Islam’ tidak menerima semua itu. Persoalan kaum Mu’tazilah buka sekedar mengasingkan diri dari mejelis guru atau dari masyarakat atau sekedar tidak suka memakai pakaian mewah. Akan tetapi, lebih jauh dari itu, mereka memiliki pemahaman atau keyakinan yang asing dari pemahaman mayoritas umat silam.
Pendapat ini, seperti mendekati kebenaran, karena dari dulu sampai sekarang fatwa-fatwa kaum Mu’tazilah tampak aneh dan berbeda dari paham Nabi dan para sahabat. Dari sini dapat dipahami bahwa mereka benar-benar Mu’tazilah, (tergelincir) dalam suatu arti kata yang sebenarnya. (Sirajuddin, 2001: 174-176).[5]
I’tiqad yang Bertentangan dengan I’tiqad Kaum Ahlussunah Wal Jama’ah
-
Baik dan Buruk Ditentukan oleh Aqal
Kaum Mu’tazilah berpendapat, bahwa buruk dan baik ditentukan oleh aqal. Mana yang baik kata aqal baiklah dia dan mana yang buruk kata aqal buruklah dia.
Kepercayaan seperti ini tidak dibenarkan oleh kaum Ahlussunah Wal Jama’ah, karena yang menentukan buruk dan baik itu adalah Tuhan dan Rasulnya, atau kataknlah Qur’an dan Sunnah, bukan aqal.
Bagi Ahlussunnah, akal itu dipakai untuk meneliti, sebagai alat pelaksana, bukan untuk menentukan suatu hukum.yang sebenar-benarnya berhak menentukan hukum-hukum adalah Qur’an dan Sunnah, yang lain tidak. Diakui oleh kaum Ahlussunah bahwa aqal itu diberi wewenang tertinggi untuk memahami tiap sesuatu, baik masalah yang kecil ataupun masalah yang besar, dan bahkan untuk mengenali wujud-Nya Allah dan sifat-sifatnya dipergunakan juga aqal pikiran.[6]
Penyataan di atas juga Telah dikenal sepanjang sejarah bahwa salah satu keistimewaan kaum Mu’tazilah adala cara mereka membentuk mazhab yang banyak mempergunakan aqal dan mengutamakan aqal dari pada Al-Qur’an dan Hadits. Dengan demikian ketika mendapatkan suatu permasalahan dan membutuhkan pemecahannya, mereka lebih memuji dan mendahulukan pertimbangan aqal, walaupun pertimbangan aqal tersebut berawanan dengan teks-teks suci, baik Al-Qur’an maupun Hadits Nabi. Bagi Mu’tazilah, akal berada di atas Al-Qur’an dan Hadits Nabi.
Sebagai contoh adalah tentan mi’raj Nabi Muhammad SAW. yang ditolak kaum Mu’tazilah karena menurut mereka bertentangan dengan aqal, sekalipun ada ayat Al-Qur’an atau Hadits sahih dari Nabi yang menyatakan keberadaannya.
Kaum Mu’tazilah menolak adanya kebangkitan di alam kubur dan siksanya. Hal ini berntentangan dengan akal karena mustahil orang yang sudah mati dan terbaring dalam tanah sesempit itudibangunkan dan disuruh duduk, walalupun ada hadits sahih yang menyatakan kejadian tersebut.[7]
Ulama-ulama Ahlussunah berpendapat bahwa aqal manusia itu tidak tetap; satu kali suatu hal diakatakan baik, tetapi tahun di muka hal itu dikatakan buruk.[8]
Oleh karena itu kaum Ahlussunnah biasa juga mengemukakan dalil-dalil, bukan saja menurut Naql (Al-Qur’an dan Hadits) tapi juga menurut aqal, sekedar alat peneliti dan alat penguat dalil, bukan untuk menetapkan hukum.[9]
- Tuhan Allah tidak punya Sifat
Kaum Mu’tazilah mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Tuhan mendengar dengan Dzat-Nya, Tuhan melihat dengan Dzat-Nya dan Tuhan berkata dengan Dzat-Nya.
Kata mereka, dasar paham ini ialah tauhid. Kalau Tuhan pakai sifat maka itu berarti Tuhan dua, yaitu Zat dan Sifat.
Paham ini bertentangan dengan paham Ahlussunah Wal Jama’ah yang mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat, bukan satu bukan dua, tetapi banyak. Ada sifat yang mesti (wajib) ada pada Tuhan, ada yang mustahil (tidak mungkin) ada pada Tuhan dan ada yang harus ada pada Tuhan. Di dalam Al-Qur’an termaktub:
هو الله الذى لااله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرّحمن الرّحيم. (الحشر: 22)
Artinya: “Dialah Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang tersembunyi dan yang terang. Dia Yang Maha Pengasih dan Penyayang.” (Al-Hasyr:22)
Dalam ayat ini terang ada nama Zat, yaitu Allah (Tuhan) dan ada sifat-Nya, yaitu “alimun” (Yang mengetahui).
Menurut tata bahasa “alimu” di sini adalah sifat bagi Allah. Semuanya orang Arab dan orang yang mengaji bahasa Arab, mengetahui hal ini. Qur’anul Karim diturunkan dalam bahasa Arab, karena itu harus diartikan Qur’an itu sesuai dengan tata bahasa Arab.[10]
- Al-Qur’an Makhluk
kaum Mu’tazilah pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriyah telah menggoncang umat Islam dengan pendapatnya bahwa Al-Qur’an itu makhluk, bukan sifat Allah yang Qadim.
Keyakinan ini merupakan kelanjutan paham mereka sebelumnya yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat.[11]
Kaum Ahlussunnah Wal Jama’ah berpendapat, bahwa Qur’an al-Krim itu kalam Allah dan sifat Allah yang Qadim, bukan makhluk yang baru.[12]
Imam Ahmad bin Hanbal dipukul separuh mati, tetapi ia tak mau mengatakan bahwa Qur’an itu makhluk tetapi tetap bibirnya mengatakan bahwa Qur’an itu kalam Allah yang Qadim.
Imam Buwaithi disiksa sampai mati, karena ia tak mau mengakui bahwa Qur’an itu makhluk, karena kalau kita biasakan mengatakan Qur’an makhluk maka hal itu bisa merembet kepada makhluknya Kalam Allah yang qadim, yang asal dari Qur’an yang kita baca sekarang ini.[13]
Berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya’ ‘Ulumuddin pada bagian “Aqaidul ‘Aqaid” dijelaskan:
“pokok ke-enam”.
‘bahwasannya Tuhan berkata dengan perkataan. Perkataan itu suatu sifat berdiri di atas Zat-Nya, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Perkataannya itu tidak sama dengan perkataan lain Tuhan, sebagaimana zat-Nya tidak serupa dengan zat lain. Perkataan yang sebenarnya ialah “kalam nafsi” yang terletak dalam diri seseorang, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kadang-kadang “dalam nafsi” itu dilahirkan dengan suara, dan huruf, kadang-kadang dengan gerak-gerik dan kadang-kadang dengan isyarat.” (Ihya’ ‘Ulumuddin Juz 1 hal. 108).
Karena itu yang hadits (baru) ialah hanya huruf-huruf atau suara-suara, tetapi Kalam Tuhan yang ditunjukkan oleh huruf-huruf dan suara-suara adalah Qadim, bukan suara dan bukan makhluk.
Hanya orang-orang Mu’tazilah berkeras kepala mengatakan bahwa Qur’an (Kalamullah) itu makhluk. Fatwa yang sesat menyesatkan ![14]
-
Pembuat Dosa Besar
Pokok permasalah yang memisahkan Washil bin ‘Atha’ dengan gurunya Syaikh Hasan Bashri, seorang tabi’in di Bashrah (wafat 110 H) ialah masalah “Orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan tidak bertobat sebelum mati.”
Imam Hasan Bashri berpendapat bahwa orang mukmin yang mengerjakan dosa besar, seperti membunuh, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Tidak menjadi kafir karena perbuatannya. Ia tetap sebagai seorang mukmin, tetapi mukmin yang durhaka. Seandainya meninggal sebelum bertaubat, dia akan dimasukkan ke neraka untuk beberapa waktu, tetapi kemudian akan dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga setelah selesai menjalani hukumannya.
Washil bin ‘Atha’, imam kaum Mu’tazilah, berpendapat lain. Menurutnya, orang mukmin yang mengerjakan dosa besar dan tidak sempat bertaubat sebelum meninggal tergolong orang yang tidak mukmin dan juga tidak kafir, melainkan dia berada di antara keduanya. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selamanya sebagaimana orang-orang kafir, hanya saja panasnya lebih ringan dari pada nerakanya orang-orang kafir. Inilah posisi atau yang disebut ileh kaum Mu’tazilah sebagai “al-Manzilah bain al-Manzilatain” yakni “tempat di antara dua tempat”[15]
Fatwa di atas tidak sesaui dengan kaum Ahlussunnah, karena menurut faham mereka tempat di akhirat hanya ada dua, kalau tidak surga ya neraka.
Orang macam itu di akhirat nanti menurut keyakinan kaum Ahlusunnah Wal Jama’ah akan mendapat bebrerapa kemungkinan:
- Bisa Jadi dosanya diampuni saja oleh Tuhan dengan kemurahan-Nya, karena Tuhan itu pengasih dan pemurah, sesudah itu ia dimasukkan ke dalam surga, tanpa hukuman.
- Bisa jai ia dapat syafa’at dari Nabi Muhammad SAW, yakni dibantu oleh Nabi Muhammad SAW sehingga ia dibebaskan Tuhan dan tidak mendapat hukuman dan langsung masuk surga.
- Kalau yang kedua di atas tidak didapat maka ia akan dihukum dan dimasukkan ke dalam nerka buat seketika, dan akhirnya di keluarkan sesudah menjalani hukuman dan dimasukkan ke dalam surga, kekal selama-lamanya karena ia seorang mu’min pada waktu didunia.
- Tuhan tidak Dapat Dilihat
Kaum Mu’tazilah memfatwakan bahw Tuhan tidak bisa dilihat walaupun dalam Surga. Karena hal itu akan menimbulkan tempat seolah-olah Tuhan ada dalam Surga atau di mana ia dapat dilihat. Imam kaum Mu’tazilah, Zamakhsyari (w. 528 H) sangat keterlaluan, sehingga dikatakannya bahwa yang ber-i’tiqad bahwa Tuhan bisa dilihat walaupun dalam surga, adalah kafir, keluar dari Islam, katanya (Lihat Tafsir Ksyaf Juz 1, hal. 179).
Paham ini berlawanan dengan paham kaum Ahlussunnah Wal Jama’ah, yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga, oleh hamba-hambanya yang shaleh yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di Dunia.
Dalilnya adalah firman Tuhan:
وجوهٌ يومئذ ناضرةٌ الى ربّها ناظرةٌ. (القيامة: 22-23)
Artinya: “Beberapa muka dihari itu bercahaya gilang-gemilang, melihat kepada Tuhannya.” (Al-Qiyamah: 22-23).
Jelas di dalam ayat ini firman Tuhan menerangkan bahwa Tuhan dapat dilihat dalam surga Jan-ntunna’im.
Maka heranlah kita melihat jalan pahamnya kaum Mu’tazilah yang mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat walaupun dalam surga.[16]
Referensi
[1] Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. Ke-1 hal. 207.
[2] Ibid, hal. 207.
[3] Ibid, hal. 207-208.
[4] Ibid, hal. 208.
[5] Ibid, hal. 208-209.
[6] Siradjuddin Abbas, I’tiqad Ahlussunah Wal Jama’ah, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), cet. Ke-8, hal. 202.
[7] Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. Ke-1 hal. 209-210.
[8] Siradjuddin Abbas, I’tiqad Ahlussunah Wal Jama’ah, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), cet. Ke-8, hal. 204.
[9] Ibid, hal. 207.
[10] Ibid, hal. 207-208.
[11] Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. Ke-1 hal. 215-216.
[12] Siradjuddin Abbas, I’tiqad Ahlussunah Wal Jama’ah, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), cet. Ke-8, hal. 210.
[13] Ibid, hal. 211.
[14] Ibid, hal. 214-215.
[15] Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. Ke-1 hal. 216.
[16] Siradjuddin Abbas, I’tiqad Ahlussunah Wal Jama’ah, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), cet. Ke-8, hal. 219.